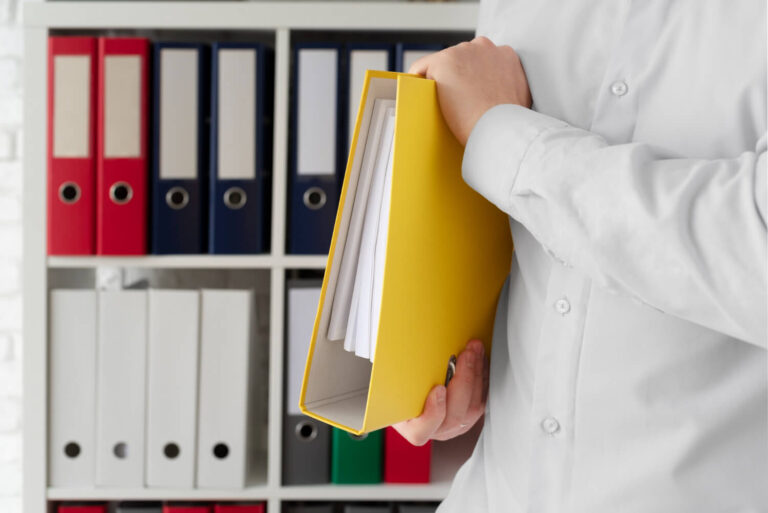Pendahuluan
Dalam setiap pemerintahan, anggaran negara atau daerah memegang peranan yang sangat penting sebagai instrumen utama dalam mengarahkan pembangunan, mengimplementasikan kebijakan publik, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Namun, di balik angka-angka rinci yang terpampang dalam dokumen anggaran, terdapat dinamika politik yang sering kali melibatkan kepentingan kelompok tertentu. Politik anggaran adalah arena pertarungan antara logika teknokratis-yang menekankan pada efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas-dengan logika politik, yang dipengaruhi oleh kalkulasi kekuasaan, patronase, serta kepentingan elektoral. Artikel ini akan membahas secara mendalam bagaimana kepentingan politik dan kebutuhan riil masyarakat berinteraksi, bertabrakan, dan kadang bersinergi dalam proses penganggaran publik.
1. Konsep Dasar Politik Anggaran
Politik anggaran dapat diartikan sebagai proses distribusi sumber daya publik melalui mekanisme legislasi dan eksekusi anggaran, di mana keputusan penentuan alokasi dana sering kali digerakkan oleh pertimbangan politik selain pertimbangan kebutuhan obyektif. Dalam literatur kebijakan publik, anggaran disebut sebagai “parent of politics” karena dari situlah mayoritas kebijakan dibiayai dan diimplementasikan. Pertama-tama, anggaran dibentuk berdasarkan rencana strategis jangka panjang, namun sering mengalami modifikasi signifikan sepanjang siklusnya karena tekanan politik. Pergeseran alokasi dari pos-pos prioritas pembangunan sosial ke anggaran kampanye politik atau proyek infrastruktur dengan dampak simbolis tinggi, misalnya, mencerminkan dominasi kepentingan politik jangka pendek. Dari perspektif teori ekonomi politik, alokasi anggaran publik mengikuti model “pork-barrel politics,” di mana legislator atau eksekutif menggunakan anggaran untuk mengamankan dukungan politik dari konstituen tertentu melalui proyek-proyek yang bersifat parsial dan terlokalisasi. Apa yang teknokrat anggap tidak efisien-misalnya, pembangunan jalan di daerah pemilihan seorang politisi padahal secara ekonomi tidak strategis-dapat menjadi prioritas karena imbal balik suara atau dukungan politik. Sementara itu, kebutuhan riil masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan layak, sering kali diakomodasi secara terbatas jika tidak mendatangkan keuntungan politik langsung.
2. Aktor dan Kepentingan dalam Politik Anggaran
Dalam proses penganggaran, terdapat beberapa aktor utama: eksekutif (pemerintah pusat atau kepala daerah), legislatif (DPR atau DPRD), birokrasi teknis (Kementerian/Lembaga atau dinas terkait), dan masyarakat sipil (LSM, media, akademisi). Setiap aktor memiliki kepentingan dan daya tawar yang berbeda.
- Eksekutif berupaya menerjemahkan visi misi pemerintahan ke dalam program dan proyek konkret. Ketua lembaga eksekutif, seperti presiden atau gubernur, memprioritaskan program-program flagship yang dapat memperkuat citra politik dan meninggalkan legacy. Selain itu, eksekutif juga harus menjaga stabilitas koalisi politik agar perjalanannya mulus di legislatif.
- Legislatif memiliki fungsi tunggal mengesahkan anggaran (power of the purse). Anggota legislatif memanfaatkan kekuasaan ini untuk memperjuangkan alokasi anggaran bagi daerah pemilihan masing-masing, menggalang basis massa, atau berdagang dukungan politik kepada eksekutif.
- Birokrasi teknis memainkan peran sebagai penyusun draf anggaran dan penerjemah kebijakan. Idealnya, mereka bekerja berdasarkan data kebutuhan obyektif-misalnya sensus penduduk untuk mengukur kebutuhan layanan kesehatan-namun dalam praktiknya, tekanan politik dari atasan dapat memengaruhi prioritas teknis.
- Masyarakat sipil melalui mekanisme partisipasi publik, musrenbang, dan sidang komisi anggaran diharapkan dapat menjadi penyeimbang. Namun, efektivitas pengawasan publik sering terkendala oleh minimnya akses informasi dan literasi anggaran.
Ketegangan antara kepentingan politis dan kebutuhan obyektif semakin tajam ketika batas antara fungsi legislasi dan eksekutif kabur. Misalnya, penggunaan dana desa yang semula bertujuan menyejahterakan masyarakat pedesaan, melalui mekanisme pergeseran prioritas dapat beralih ke proyek yang menguntungkan sponsor politik lokal.
3. Siklus dan Proses Perencanaan Anggaran
Siklus anggaran publik umumnya terdiri dari beberapa tahap: perumusan kebijakan, perencanaan, pengesahan legislasi, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada setiap tahap, politik anggaran berpotensi menimbulkan manipulasi kepentingan.
- Perumusan Kebijakan (Policy Formulation): Tahap awal di mana eksekutif merancang prioritas pembangunan. Dalam proses ini, survei kebutuhan dan data ekonomi menjadi dasar, namun draf awal cenderung disiapkan untuk memudahkan lobi politik di tahap selanjutnya.
- Perencanaan (Planning): Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) disusun oleh birokrat teknis. Rapuhnya integritas data-akibat manipulasi statistik atau skema “padanan anggaran”-bisanya terjadi saat kebutuhan diestimasi untuk mengakomodasi kepentingan politisi.
- Pengesahan Legislasi (Budget Approval): Draf anggaran dibahas dan disahkan oleh DPR/DPRD. Di sini, terjadi negosiasi intensif antara eksekutif dan legislatif. Politik bargaining (tawar-menawar) mendorong munculnya pagu-pagu tambahan untuk kepentingan proyek tertentu.
- Pelaksanaan (Execution): Setelah disahkan, birokrasi bertugas melaksanakan program. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sering muncul untuk melayani kepentingan kelompok elit melalui pengadaan fiktif atau kontrak menyimpang.
- Pengawasan (Oversight & Evaluation): Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP, KPK, serta mekanisme audit publik bertugas mengawasi. Namun, efektivitas pengawasan masih terbatas oleh hambatan administratif dan politik.
4. Ketegangan antara Kepentingan dan Kebutuhan
Setiap kebijakan anggaran menghadapi dilema antara tuntutan kepentingan politik jangka pendek dan kebutuhan jangka panjang masyarakat. Misalnya, peningkatan anggaran kampanye kesehatan atau air bersih hanya menjelang pemilu dapat menunjukkan kepedulian, tetapi berpotensi terhenti setelah momentum politik berlalu. Dalam konteks desentralisasi, alokasi dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) sering menjadi alat politik antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat memanfaatkan DAK untuk mengendalikan agenda politik daerah, sementara daerah menggunakan DAU untuk membiayai kebutuhan operasional. Ketergantungan anggaran daerah pada alokasi pusat bisa mengurangi kemandirian fiskal, sehingga kebutuhan unik lokal tidak selalu terakomodasi secara optimal. Adopsi praktik angel budgeting, yaitu menempatkan proyek-proyek prioritas pemerintahan pada tahap akhir siklus anggaran, juga menunjukkan bagaimana kebutuhan nyata kerap tersisih. Administrasi yang mempercepat pelepasan dana di akhir tahun untuk memenuhi target fisik tanpa kajian kelayakan jangka panjang sering menimbulkan pemborosan dan inefisiensi.
5. Studi Kasus: Proyek Infrastruktur vs Subsidi Sosial
Sebagai ilustrasi, kita dapat melihat alokasi anggaran infrastruktur jalan tol yang memakan porsi besar di beberapa provinsi. Dana yang tersedot untuk membangun jalan tol eksklusif sering menimbulkan kontroversi ketika masyarakat sekitar belum mendapatkan akses jalan desa memadai. Di sisi lain, program subsidi listrik atau kartu sembako-yang jauh lebih langsung meringankan beban ekonomi masyarakat miskin-sering dipangkas jelang pembahasan anggaran akhir. Contoh konkret dapat diambil dari anggaran provinsi X pada tahun anggaran 2024, di mana anggaran infrastruktur meningkat 35% dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan anggaran kesehatan hanya naik sebesar 5%. Ketimpangan ini memunculkan protes LSM yang menilai bahwa kenaikan anggaran infrastruktur lebih menguntungkan jaringan kontraktor ketimbang sektor kesehatan yang sangat memerlukan peningkatan pelayanan primer.
6. Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi
Untuk mengurangi dominasi kepentingan politik jangka pendek dan menjamin alokasi anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan obyektif masyarakat, diperlukan berbagai pendekatan terpadu:
6.1 Digitalisasi dan Portal Transparansi Pengembangan portal anggaran terbuka (open budget portal) yang memuat seluruh tahapan perencanaan, realisasi, dan evaluasi pengeluaran pemerintah dapat mempersempit ruang bagi praktik manipulasi data. Pemanfaatan dashboard interaktif, laporan real-time, dan infografis membantu warga memahami alur anggaran dan memungkinkan media serta LSM melakukan audit publik dengan cepat.
6.2 Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Lokal Menerapkan anggaran partisipatif yang lebih representatif-dengan sasaran kelompok marginal dan wilayah terpencil-membutuhkan pelatihan fasilitator, peningkatan literasi anggaran di tingkat desa/kelurahan, serta penggunaan teknologi seluler untuk menjaring aspirasi. Dengan demikian, alokasi dana akan mencerminkan kebutuhan riil lapangan, bukan hanya prioritas elit politik.
6.3 Penguatan Penegakan Hukum dan Sanksi Diperlukan mekanisme koordinasi lebih erat antara aparat penegak hukum (KPK, BPK, Kejaksaan) dan lembaga audit internal (BPKP), serta pemberian status prioritas kasus korupsi anggaran. Revisi regulasi untuk memperberat sanksi administratif dan pidana bagi pelaku KKN dalam pengadaan barang/jasa akan memberikan efek jera.
6.4 Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance-Based Budgeting) Mengaitkan alokasi anggaran dengan capaian indikator kinerja sektoral-misalnya penurunan angka kematian ibu, peningkatan akses sanitasi, atau indeks kualitas pendidikan-akan mendorong birokrasi fokus pada hasil (outcome) ketimbang volume anggaran (output). Skema insentif bagi unit kerja yang mampu menunjukkan efisiensi dan efektivitas program perlu disosialisasikan.
6.5 Pengembangan Indikator Kebutuhan Obyektif dan Alokasi Berkeadilan Menyusun indikator kebutuhan sektoral berbasis data statistik mutakhir (misalnya Indeks Kemiskinan Multidimensi, skor kerentanan bencana, dan indeks kematangan layanan digital) menjadi landasan alokasi minimal per wilayah. Metode alokasi berbasis formula objektif meminimalisir intervensi politis dan menjamin distribusi yang lebih merata.
6.6 Desentralisasi Fiskal yang Bertanggung Jawab Meningkatkan porsi penerimaan asli daerah (PAD) dan memperluas kewenangan pemungutan pajak lokal, disertai transfer dana alokasi umum (DAU) yang fleksibel, memungkinkan pemerintah daerah membiayai kebutuhan spesifik masyarakat. Namun, perlu disertai persyaratan transparansi laporan dan kemampuan pengelolaan fiskal agar desentralisasi tidak menjadi ladang korupsi.
6.7 Pembentukan Forum Multi-Stakeholder Pembentukan dewan penganggaran independen yang melibatkan pemerintah, legislatif, akademisi, organisasi profesi, dan wakil masyarakat sipil dapat berfungsi sebagai ruang deliberasi sebelum penetapan anggaran. Forum ini juga dapat menyusun rekomendasi teknis, mereview usulan, serta memantau realisasi dengan melibatkan auditor eksternal. Dengan implementasi rekomendasi di atas, kerangka kebijakan anggaran akan bergeser dari model top-down yang mudah dimanipulasi menuju tata kelola yang partisipatif, akuntabel, dan berfokus pada hasil jangka panjang.
Kesimpulan
Politik anggaran tidak bisa dilepaskan dari realitas politik dan struktur kekuasaan dalam pemerintahan. Meski logika politik kerap mendominasi, kebutuhan obyektif masyarakat harus dijadikan tolok ukur utama dalam setiap proses penganggaran. Reformasi yang meliputi digitalisasi data, anggaran berbasis kinerja, penguatan sanksi hukum, serta peningkatan partisipasi publik dapat mengurangi potensi penyimpangan dan memastikan anggaran menyentuh sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.
Lebih lanjut, komitmen politik dari pucuk pimpinan hingga birokrat teknis mutlak diperlukan untuk menerapkan kebijakan ini secara konsisten. Akademisi dan media juga memiliki peranan vital dalam menjaga momentum transparansi dan akuntabilitas. Ke depan, pemerintahan yang responsif harus mampu menggabungkan kecanggihan teknologi, pendekatan partisipatif, dan penegakan hukum yang tegas untuk menjawab tantangan pembangunan dan keadilan sosial. Dengan demikian, politik anggaran yang seimbang antara kepentingan politik dan kebutuhan masyarakat tidak hanya menjadi idealisme, tapi dapat diwujudkan melalui reformasi struktural dan budaya kerja pemerintahan. Hanya dengan sinergi antara semua pemangku kepentingan, tujuan utama anggaran-yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat secara merata-dapat tercapai secara berkelanjutan.
![]()